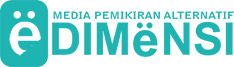Poligami kerap menjadi topik perdebatan hangat di masyarakat Muslim. Sebagian kalangan melihatnya sebagai praktik yang sah dan dibenarkan agama, sementara yang lain menilai poligami lebih banyak menghadirkan luka sosial, terutama bagi perempuan. Perdebatan ini tidak hanya menyentuh ranah hukum Islam, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, dan psikologis.
Dalam perspektif hukum Islam, poligami memang memiliki landasan yang jelas, merujuk pada Surah An-Nisa ayat 3 yang memberikan ruang bagi seorang laki-laki untuk menikahi hingga empat istri dengan syarat mampu berlaku adil. Namun, interpretasi terhadap ayat ini terus menjadi perdebatan, karena keadilan yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan materi, tetapi juga menyangkut aspek emosional dan perhatian. Hal ini membuat para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan sejauh mana poligami dapat dijalankan tanpa menimbulkan mudarat bagi pihak-pihak yang terlibat.
Di sisi lain, dari aspek sosial dan psikologis, poligami sering dikritik karena berpotensi melahirkan ketidakstabilan dalam rumah tangga. Rasa cemburu, ketidakadilan emosional, dan persaingan antar istri kerap muncul, sehingga memunculkan dampak psikologis yang serius, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Lebih jauh, dalam masyarakat modern, poligami sering dipandang tidak selaras dengan nilai-nilai kesetaraan gender yang tengah diperjuangkan. Perempuan dianggap lebih rentan mengalami marginalisasi dalam perkawinan poligami, karena posisi mereka seringkali menjadi subordinat di bawah otoritas laki-laki.
Dalam konteks negara modern, poligami bahkan seringkali berhadapan dengan hukum positif yang lebih menekankan monogami sebagai asas perkawinan. Contohnya di Indonesia, meskipun Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 masih memberikan peluang poligami dengan syarat tertentu, tetapi praktiknya dipersulit agar tidak dilakukan secara sembarangan. Dengan demikian, poligami bukan hanya sekadar isu agama, melainkan juga menyangkut relasi sosial, hak asasi manusia, serta perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak.
Poligami sebagai salah satu praktik perkawinan dalam tradisi Islam selalu menimbulkan polemik yang kompleks. Meskipun memiliki landasan hukum agama, praktik ini tidak bisa dilepaskan dari realitas sosial dan hukum positif di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa asas perkawinan di Indonesia adalah monogami, namun poligami tetap dimungkinkan dalam kondisi tertentu. Pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa seorang suami dapat beristri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak-pihak terkait dan diizinkan oleh pengadilan. Akan tetapi, syarat yang ditetapkan cukup ketat, misalnya harus mendapat persetujuan istri pertama, adanya alasan yang sah, serta kemampuan suami untuk memberikan nafkah dan berlaku adil. Aturan ini memperlihatkan bahwa negara pada dasarnya berusaha membatasi praktik poligami agar tidak menimbulkan ketidakadilan, khususnya terhadap perempuan.
Jika ditinjau dari perspektif gender, poligami menimbulkan berbagai polemik karena memperlihatkan ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Dalam budaya patriarkis, poligami dianggap sebagai hak istimewa laki-laki yang tidak bisa digugat. Padahal, jika dilihat dari sudut pandang keadilan gender, praktik ini rentan menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Perempuan seringkali tidak memiliki ruang yang setara untuk menyuarakan pendapatnya, baik dalam menerima maupun menolak poligami. Dalam banyak kasus, persetujuan istri pertama hanya formalitas belaka karena adanya tekanan sosial, ekonomi, maupun psikologis. Hal ini jelas menunjukkan bukti kesenjangan gender yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan.
Dalam perspektif feminisme, poligami dipandang sebagai institusi sosial yang potensial mengekalkan dominasi laki-laki jika tidak diawasi dengan ketat. Feminisme liberal, misalnya, menekankan bahwa setiap individu — baik laki-laki maupun Perempuan — memiliki hak yang sama untuk menentukan pilihan hidup, termasuk dalam perkawinan. Poligami, dalam pandangan ini, hanya dapat diterima jika semua pihak yang terlibat benar-benar menyetujuinya tanpa paksaan, serta memiliki kesempatan yang setara untuk memperoleh kebahagiaan dan keadilan. Sementara itu, feminisme radikal melihat poligami sebagai bentuk penindasan secara struktural terhadap perempuan, karena hampir tidak ada ruang bagi perempuan untuk memiliki “hak poligami” yang sama. Dengan demikian, poligami lebih dipandang sebagai bentuk ketidakadilan sistemik yang perlu dibatasi demi melindungi hak-hak perempuan.
Namun, penting untuk digarisbawahi bahwa perspektif feminisme tidak serta-merta menganggap perempuan sebagai korban pasif. Dalam banyak kasus, perempuan juga memiliki agensi untuk menolak atau menerima poligami sesuai dengan pilihan hidupnya. Feminisme kontemporer lebih menekankan pada upaya menciptakan kesetaraan struktural agar perempuan tidak dipaksa masuk dalam sistem perkawinan yang merugikan dirinya.
Dalam konteks hukum di Indonesia, pengaturan poligami yang mensyaratkan izin istri pertama dan persetujuan pengadilan merupakan langkah positif untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan. Meski demikian, masih terdapat celah dalam implementasi hukum, terutama di daerah-daerah dengan budaya patriarkis yang kuat, di mana suara perempuan seringkali tidak dianggap penting.
Jika dilihat dari sisi keadilan sosial, praktik poligami yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan masalah serius. Perempuan berpotensi mengalami tekanan psikologis seperti kecemburuan, rasa terpinggirkan, hingga penurunan kualitas hidup. Anak-anak yang lahir dari keluarga poligami juga sering menghadapi dampak sosial berupa kurangnya perhatian, konflik rumah tangga, dan ketidakstabilan emosional.
Oleh karena itu, dari perspektif feminisme, solusi yang ditawarkan adalah menciptakan kerangka hukum yang lebih kuat untuk melindungi hak-hak perempuan, memastikan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan, serta memperkuat nilai kesetaraan dalam perkawinan. Dengan cara ini, poligami tidak lagi dilihat sebagai hak istimewa laki-laki, tetapi sebagai pilihan yang hanya dapat dijalankan ketika semua pihak setara dan memperoleh perlindungan hukum serta sosial yang adil.
Poligami merupakan isu yang kompleks karena menyentuh ranah agama, sosial, hukum, dan psikologis. Meski Islam membolehkannya dengan syarat keadilan, praktik di lapangan sering menimbulkan ketidaksetaraan, terutama bagi perempuan. UU No. 16 Tahun 2019 telah menegaskan asas monogami, namun tetap memberi ruang terbatas untuk poligami dengan syarat ketat.
Dari perspektif gender dan feminisme, poligami harus dikaji secara kritis agar tidak memperkuat patriarki. Perempuan harus dipandang setara, bebas dari tekanan, dan dilindungi hak-haknya. Dengan demikian, poligami hanya dapat diterima jika benar-benar menjunjung kesetaraan dan keadilan bagi semua pihak.
Penulis: Gea Oktavia Ramadhani
Ilustrator: Cindy Dewi Kusuma
Editor: Mustofa Ismail