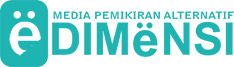Gerakan mahasiswa sejak dulu selalu dipandang sebagai motor perubahan. Kampus dan organisasi mahasiswa seharusnya menjadi ruang dialektika, tempat mengkaji permasalahan lokal, daerah, maupun nasional. Dari problem petani yang kehilangan lahan, buruh yang tertindas upah murah, sampai isu nasional seperti ketimpangan pendidikan dan kebijakan yang timpang. Diskusi bukan hanya soal teori, tapi pemetaan realitas, membaca situasi, dan merumuskan strategi perubahan. Namun, yang terjadi justru sebaliknya.
Di Tulungagung, gerakan mahasiswa berubah rupa. Bukan lagi barisan intelektual penggerak perubahan, melainkan organ kampus yang sibuk mengurus backdrop, konsumsi, dan proposal dana. Kritik memang masih terdengar, tetapi berhenti di forum seminar, tidak menjelma aksi nyata di jalanan. Asumsinya, orientasi mahasiswa kini lebih diarahkan pada sertifikat dan pengalaman organisasi, tradisi kritis berhenti sebagai wacana akademik, serta ada ketakutan terhadap represi jika turun ke jalan. Maka tidak heran, jalanan sepi, rakyat tetap sendiri. Sementara, mahasiswa lebih nyaman berperan sebagai penyelenggara acara ketimbang penggerak perubahan.
Padahal sejarah Indonesia tidak pernah lahir dari seminar. Dari tahun 1966, 1978, hingga 1998, mahasiswa turun ke jalan, menggetarkan kekuasaan, dan menyambung lidah rakyat. Kini, mahasiswa di daerah justru kehilangan nyali. Diskusi berhenti jadi wacana, kritik berakhir di notulensi, dan rakyat kecil tetap menanggung beban sendirian.
Kalau Mahasiswa diam, siapa lagi yang akan bersuara?
Pernyataan yang sempat viral soal Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, yang dianggap menyebut guru sebagai “beban negara” memang sudah dibantah. Video itu ternyata hasil potongan tidak utuh bahkan deepfake dari pidatonya di ITB, 7 Agustus 2025. Sri Mulyani menegaskan, ia tidak pernah menyebut guru sebagai beban negara. Namun, kegaduhan itu membuka luka lama. Bagaimana negara memperlakukan guru bukan sebagai pilar peradaban, melainkan sekadar pos anggaran yang bisa ditekan.
Padahal, anggaran pendidikan nasional sudah mencapai Rp. 724,3 triliun. Janji kenaikan gaji ASN dan tunjangan guru non-ASN juga berulang kali diumbar. Tetapi realitas di lapangan tetap ironis. Data nasional menunjukkan 74,3% guru honorer menerima gaji di bawah Rp. 2 juta per bulan, bahkan 20,5% di antaranya hanya mendapat kurang dari Rp. 500 ribu. Guru non-sertifikasi rata-rata hanya mendapat insentif Rp. 300 ribu – Rp. 500 ribu per bulan. Sedangkan yang sudah bersertifikasi (PPG) memperoleh Tunjangan Profesi Guru (TPG) sekitar Rp 2 juta per bulan, itu pun di luar gaji pokok dari sekolah.
Di Tulungagung, kondisinya lebih miris. Liputan iNews pada Januari 2024 menerangkan bahwa Guru PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) paruh waktu hanya menerima gaji Rp. 100 ribu hingga Rp. 350 ribu per bulan, jauh dari standar hidup minimum. Insentif dari Pemkab pun yang sebelumnya hanya Rp. 350 ribu untuk SD dan Rp. 400 ribu untuk SMP, itupun sekadar mengganti ongkos transportasi.
Fakta ini menohok nurani. Bagaimana mungkin bangsa ini menyiapkan generasi tangguh jika gurunya sendiri masih diperlakukan seolah beban. Anggaran pendidikan besar, tapi martabat guru kecil. Selama guru terus dipandang sekadar angka dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), maka wajar jika pendidikan hanya jadi retorika politik tanpa fondasi nyata.
Kontras dengan nasib guru, anggota DPR hidup dengan kemewahan. Gaji dan tunjangan mereka bisa mencapai Rp. 100 juta per bulan. Namun, fungsi DPR lebih sering menyerupai tukang stempel pemerintah. Mereka jarang berdiri di sisi rakyat, apalagi berani menolak kebijakan yang jelas-jelas menindas. Sementara buruh bekerja 12 jam sehari hanya untuk puluhan ribu rupiah, DPR dengan mudah mengantongi Rp 3 juta per hari tanpa harus berkeringat. Demonstrasi buruh dan mahasiswa pada 25 Agustus 2025 di Jakarta membuktikan amarah rakyat yang sudah menumpuk. Namun, jawaban negara tetap sama: gas air mata, tameng polisi, dan telinga yang tertutup rapat.
Di sisi lain, rakyat kecil terus saja menjadi korban. Petani digusur oleh tambang, nelayan dilindas industri besar, pedagang kecil digilas oleh retail modern. Suara mereka jarang sekali sampai ke meja kebijakan. Elit politik lebih sibuk memperjuangkan tunjangan rumah, kendaraan dinas, dan fasilitas mewah. Situasi ini bukan sekadar ketimpangan sosial-ekonomi. Ia sudah menjelma menjadi penghinaan terang-terangan terhadap rakyat.
Dalam situasi inilah, mahasiswa seharusnya tidak boleh diam. Antonio Gramsci dalam salah satu karyanya menyebutkan mahasiswa harus menjadi intelektual organik. Intelektual yang tidak hanya memproduksi ilmu di menara gading, tetapi juga menghubungkan pengetahuan dengan denyut nadi rakyat. Jurgen Habermas menegaskan pentingnya ruang publik kritis, tempat masyarakat dapat berdebat secara rasional dan menyuarakan kepentingannya, tanpa dominasi elit yang membungkam. Pedagogy of the Oppressed karya Paulo Freire mengingatkan bahwa pendidikan sejati bukan sekadar refleksi, tetapi juga aksi—yakni proses pembebasan yang menuntut keterlibatan aktif dalam perubahan sosial.
Sudah cukup mahasiswa Tulungagung bersembunyi di balik seminar. Diskusi harus jadi bahan bakar aksi, bukan arsip kegiatan. Kampus harus kembali jadi markas perjuangan, bukan panggung acara glamor. Kalau mahasiswa ingin disebut gerakan, mereka harus berani menyuarakan nasib guru yang dipinggirkan, berani melawan DPR yang rakus anggaran, dan berdiri di sisi rakyat kecil yang ditindas.
Mahasiswa tidak boleh puas hanya menjadi komentator pasif di pinggir panggung perubahan. Kritik tanpa aksi hanyalah kebisingan kosong, seakan kembang api di malam gelap tanpa jejak. Gerakan mahasiswa Tulungagung kini dihadapkan pada pilihan sebagai Event Organizer kampus yang sibuk proposal dana, atau kembali merapat ke jalan rakyat dengan keberanian.
Dalam setahun terakhir, mereka dua kali turun ke jalan. 26 Agustus 2024, aliansi mahasiswa dan masyarakat menggelar aksi di DPRD dengan enam tuntutan, mulai dari pengawalan putusan MK Pilkada hingga pendidikan gratis, mitigasi bencana, dan ekonomi pro-rakyat. Ketua DPRD menandatangani tuntutan mereka, meski realisasi masih jauh. 15 Juli 2025, puluhan mahasiswa bersama LKHN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) menuntut transparansi anggaran Sekda 2024, mengecam kejanggalan laporan keuangan, dan menolak jawaban normatif. Aksi ini ditutup dengan pembakaran ban sebagai simbol kekecewaan.
Fakta ini menunjukkan gerakan mahasiswa Tulungagung belum mati, tapi masih rapuh. Aksi mereka sporadis, lebih mirip momentum tahunan ketimbang gerakan yang konsisten. Setelah jalanan sepi, mahasiswa kembali tenggelam dalam rutinitas kampus dan birokrasi. Gerakan ini harus menegaskan jati dirinya bukan Event Organizer kampus, melainkan kekuatan moral bersama rakyat, mengawal kebijakan, dan jadi pengingat keras bagi penguasa. Hanya dengan itu mahasiswa layak disebut agen perubahan, bukan penonton sejarah.
“Sejarah tidak pernah mencatat seminar yang megah. Sejarah hanya mencatat siapa yang berani berdiri bersama rakyat dengan gagah.”
Penulis: David Yogi Prastiawan
Editor: Mustofa Ismail