Manusia adalah mahluk pemakan segalanya. Karena makan, manusia jadi saling memakan dengan sangat rakusnya.
Kembali menghadirkan Mahuze dalam ruang diskusi ada yang beranggapan sudah lewat dan klise untuk dibahas. Tapi, menurut saya celaka jika kita melewatkan diskusi itu begitu saja. Sesungguhnya apa yang terjadi pada suku Mahuze adalah buntut ketakutan umat manusia pada apa yang diramalkan Malthus soal krisis pangan.
Sampai sekarang solusi mengatasi krisis pangan belum juga berhasil. Revolusi hijau jilid I oleh Norman Borlang menuai hasil spektakuler di awal namun gagal mengatasi krisis pangan untuk selanjutnya, begitu juga Revolusi hijau jilid II yang diinisiasi oleh Robert Fradey. Proyek yang justru membawa masalah baru berupa turunnya jumlah air secara signifikan, kerusakan tanah akibat pupuk dan pestisida, gejala keracunan dan kanker menyebar, dan biaya pertanian yang semakin tinggi. [1]
Penetrasi Revolusi Hijau pertama di Indonesia dilaksanakan dalam bentuk BIMAS atau bimbingan masa tahun 1970. Bimas adalah suatu paket program pemerintah yang berupa teknologi pertanian, masukan bibit, pupuk, pestisida dan bantuan kredit. Ketika peserta BIMAS menurun, pemerintah mengelontorkan program baru INMAS (intensifikasi masa) yakni suatu program kredit sebagai lanjutan bagi peserta Bimas. Tahun 1979 program baru lagi diberlakukan yakni INSUS (intensifikasi khusus), tujuannya untuk mendorong petani menanam tanaman sambil mengontrol hama padi.
Hasil kuantitatif Revolusi Hijau di Indonesia memang menakjubkan. Di satu pihak pertanian di Jawa mampu memproduksi dua kali lipat padi dari hasil pertanian Jawa tahun 1960-an. Jawa menyumbangkan lebih dari rata rata kontribusi dibanding daerah lain di Indonesia, dan oleh karena itu memainkan peran utama dalam perubahan status Indonesia dari pengimpor terbesar beras dan tahun 1985 menjadi mandiri. Fakta sekarang, Revolusi Hijau di Indonesia hanya berhasil di awal saja. Setelah swasembada beras tahun 1985 Indonesia kembali menjadi negara pengimpor beras terbesar dunia hingga sekarang
Konversi hutan 1,2 juta Ha menjadi ‘sawah’ yang dicanangkan Jokowi dalam 3 tahun mendatang, terhitung per 10 Mei 2015, untuk menjaga ketersediaan pangan bagi 2,5 juta masyarakat Indonesia, lalu untuk memberi makan 10 Milyar penduduk dunia. Dengan luasan tersebut diperkirakan akan diperoleh produksi padi 24 ton per hektar per tahun maka secara keseluruhan akan dihasilkan sekitar 24 juta ton per tahun. Jumlah ini sama dengan 30 % produksi padi nasional (produksi padi nasional 70,83 juta ton per tahun).[2]
MIFEE Proyek Ketahanan Pangan?
Di bulan April 2006, sebuah proyek bertajuk Merauke Integrated Rice Estate (MIRE) diluncurkan sebagai bagian dari MP3EI (Master Plan Perluasan dan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia). Bagi SBY, proyek ini adalah ide cemerlang bahwa Indonesia akan memiliki sebuah ‘pabrik beras’ yang tidak hanya masif dalam luasan proyek namun juga dalam skala produksi.[3] Untuk menopang MIRE pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28, Tahun 2008 yang secara detail menjadikan kabupaten Merauke sebagai pusat proyek, dan membaginya ke dalam enam daerah utama yang masing-masing akan menjadi daerah industri dengan tanaman spesifik.
Di tahun yang sama, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 diluncurkan untuk mempercepat realisasi MIFEE. Inpres ini secara spesifik meminta Badan Pertanahan Nasional bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke untuk segera melakukan pemetaan, pengukuran dan pembagian enam daerah kunci.
Di tahun 2010, Rezim SBY kemudian mengemas proyek MIRE dengan sebuah rencana yang lebih glamour: Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE). Pemerintah mengeluarkan PP No.18, Tahun 2010 yang secara khusus memberikan perhatian terhadap MIFEE serta proyeksi tentang keuntungan nasional yang bakal didapat dari pajak dan keuntungan lain jika proyek ini berjalan.

Proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) di era pemerintahan SBY kemudian dilanjutkan di era Jokowi. Tidak tangung-tanggung, Jokowi menarget 1,2 juta Ha areal hutan Merauke harus dikonversi menjadi sawah dalam waktu 3 tahun mendatang.
Jauh sebelum MIRE dan MIFEE Belanda pada tahun 1951 sudah memulai proyek menanam padi juga atas nama ‘ketahanan pangan’ diatas area 700 Ha. Proyek ini diteruskan di bawah pemerintahan Indonesia hingga 2015. Dalam kurun waktu 66 tahun, di Merauke tercetak 43 ribu ha sawah artinya terjadi penambahan 42.300 ha.[4] Sungguh edan 3 tahun waktu yang dicanangkan Jokowi untuk bisa menghasilkan luas lahan hingga 1,2 juta Ha. Sehingga dalam pidato Jokowi mengatakan proyek ini membutuhkan dana tidak hanya milyaran tapi triliunan.
Pertanyaannya, apakah benar proyek MIFEE semata-mata sebagai solusi memenuhi ketersediaan ‘nasi’? Sayangnya tidak, Andre Barahamin menemukan data yang mematahkannya. Total luas lahan yang dikorbankan untuk MIFEE mencapai 1.927.357 hektar, atau hampir dua juta hektar. Dari total 973.057 hektar (50.48 persen) digunakan untuk industri perkebunan kayu, 2.800 hektar (0.14 persen) dianggarkan untuk pengolahan kayu, 433.187 hektar (22.47 persen) dikorbankan untuk perkebunan sawit, 415.094 hektar (21.53 persen) diberikan untuk industri perkebunan tebu yang produksi akhirnya adalah gula, dan 103.219 hektar (5.38 persen) untuk sawah padi beras. Perbandingan statistik sederhana serta ijin konsesi alih fungsi hutan di atas menunjukkan bahwa MIFEE sejak awal tidak bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, seperti digembor-gemborkan oleh propaganda pemerintah. Sebaliknya, ekspansi dan perampasan lahan ini semata-mata ditujukan untuk memenuhi kebutuhan ekstraktif korporasi semata.[5]
Efek Domino
Mega-proyek MIFEE akan membawa dampak buruk bagi Papua. Pertama, proyek MIFEE dan proyek yang mendahuluinya membabat 2,5 juta Ha, berpotensi menciptakan krisis pangan. Malind-Anim sebagai suku yang memiliki ketergantungan besar terhadap hutan akan menjadi korban serius proyek MIFEE. Secara drastis ketersediaan sagu dan hewan buruan berkurang karena alih fungsi hutan untuk kepentingan industri pertanian. Ancaman kekurangan gizi bakal melanda Malind-Anim.
Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke pada tahun 2013 mencatat naiknya jumlah kematian ibu dan anak di Kabupaten Merauke secara tajam (15 persen). Setelah MIFEE resmi diluncurkan, Forest People Programme mencatat mewabahnya malnutrisi yang berujung pada kematian. Di dusun Zanegi, distrik Malind, tercatat 5 orang anak meninggal dunia karena kekurangan gizi.
Kedua, proyek MIFEE jelas-jelas akan mendeforestasi luas hutan di Merauke. Dalam berbagai publikasi yang berhasil dikumpulkan, MIFEE ditargetkan secara bertahap merampas sekitar 2.5 juta hektar hutan alam dan lahan gambut yang berada di wilayah ulayat Malind-Anim. Total luas lahan ini rencananya akan didistribusikan untuk industri pangan (50 persen), industri sawit (20 persen) dan industri tebu (30 persen). [6]
Sesuai dengan pola ruang Kabupaten Merauke, luas daratan Kabupaten Merauke adalah 4.670.163 Ha. Dari luas tersebut yang sebelumnya dialokasikan untuk kawasan perlindungan seluas 2.455.694 Ha dan untuk kepentingan investasi seluas 1.598.822 ha akan dibalik, 2,5 juta Ha yang justru untuk investor. Efeknya, persentase status emisi Kabupaten Merauke terhadap Provinsi Papua kini mencapai 45,29 persen dan status emisi Kabupaten Merauke terhadap nasional mencapai 3,6 persen.[7]
Pada tahun 2005 hingga 2009, luas hutan Papua 42 juta ha. Tiga tahun kemudian menyusut menjadi 30,07 juta ha. Data pemerintah menyebutkan, setiap tahun rata-rata deforestasi di Papua 143.680 ha. Sedangkan laju deforestasi untuk Papua Barat per tahun 25 persen atau 293 ribu ha.[8]
Ketiga, Semakin sulitnya mencari bahan pangan, membuat banyak keluarga Malind-Anim terpaksa mesti menyeberang ke sebagian kecil hutan yang dimiliki keluarga lain. MIFEE memicu konflik sosial antar marga dan suku yang lebih besar. Sudah jamak konflik antar suku terjadi akibat melanggar batas territorial. Upacara adat yang biasa dilakukan untuk meredam konflik antar marga juga semakin sulit karena lokasi-lokasi penting bagi Malind-Anim telah terampas.

Perusahaan sawit yang saat ini sudah memengaruhi habitat kali Bian di Merauke. “Dulu Kali Bian airnya bisa diminum. Airnya bersih sebelum adanya perusahaan (Sawit). Tapi dengan adanya perusahaan, kami tidak bisa lagi mimun. Untuk minum kami harus pergi beli air atau masak air dari sumur”, ujar salah satu Marga Mahuze dalam film dokumenter The Mahuze.

Keempat, kegagalan dan akibat yang ditimbulkan Revolusi Hijau di Filipina, negara percontohan revolusi hijau di Asia kini mengancam Papua. Varietas IR‑8 yang dikeluarkan tahun 1966, mengalami penderitaan serius diserang oleh hama antara tahun 1968–1969, dan pada tahun 1970–1971 wereng tungro menghancurkan IR‑8 diseluruh Pilipina.
Varietas IR-20 selanjutnya diciptakan dalam rangka menggantikan IR‑8. Pada tahun 1971–1972 IR-20 diperkenalkan sebagai bibit baru yang tahan terhadap hama dan tungro. Namun pada tahun 1973 hama belalang wereng menghancurkan jenis IR-20 di hampir seluruh propinsi di Filipina. Setelah itu varietas baru pun dilemparkan, yakni IR-26. Nasib IR-26 ini juga tidak jauh beda, tahun 1974–1975 juga hancur diserang hama belalang jenis baru. Tahun 1976, varitas baru pun diciptakan, yakni IR-36, dan setiap ditemukan bibit unggul baru, selalu saja musuh baru muncul.

Kelima, dalam pangkur (panen sagu), perempuan memiliki peran yang sama dengan laki-laki. Mulai dari memotong kayu sampai menepung sagu, semua dilakukan bersama, perempuan dan laki-laki. MIFEE bisa mengubah tatanan sosial tersebut dengan menempatkan perempuan di area domestik.
Revolusi industri dan revolusi hijau di belahan dunia telah mengubah peran perempuan terbatas di dalam rumah. Pabrik-pabrik lebih memilih mempekerjakan laki-laki daripada perempuan. Meskipun ada kesempatan perempuan bekerja, soal upah dia selalu kalah dibanding laki-laki.
Kemudian, urusan bertani diasosiasikan sebagai pekerjaan berat, sehingga ‘dimitoskan’ hanya laki-lakilah yang mampu mengambil pekerjaan itu. Perempuan yang distereotipkan sebagai kaum lemah, ibu rumah tangga, istri yang setia menunggu suaminya pulang kerja, tidak dimungkinkan mengambil peran.
Keenam, masyarakat Merauke memiliki indigeneous bahwa hidup harus menyatu dengan alam. Hutan menjadi sumber pangan yang menyediakan sagu, hewan buruan, buah-buahan dan kebutuhan hidup lain. Dalam kosmologi Malind-Anim, hutan dipandang sebagai ‘Ibu’ yang memberikan kehidupan serta pintu religius berhubungan dengan Dema.
Keterikatan Malind-Anim dengan hutan juga dapat dikenali melalui pemaknaan dari tiap-tiap marga (fam) Malind-Anim dengan tumbuhan atau hewan yang terdapat dalam hutan. Semisal marga Gebze yang dilambangkan dengan pohon kelapa, Samkakai yang disimbolkan oleh kangguru, fam Mahuze yang ditandai oleh sagu, Kaize yang berasosiasi dengan kasuari atau babi hutan. Kehilangan simbol klan bagi Malind-Anim merupakan tragedi keterputusan sejarah antara dirinya dengan kebudayaannya. Menggantikan hutan sagu dengan sawit, sawah padi atau perkebunan tebu berarti aksi langsung penghancuran terhadap perangkat penunjang kosmologi Malind-Anim, yang berimplikasi pada pemusnahan kebudayaan (etnosida) Malind-Anim secara keseluruhan.[9]
Di berbagai kota besar, pemerintahnya berusaha melakukan diversifikasi pangan termasuk mengeluarkan aturan satu hari tanpa nasi, sebaliknya di daerah dimana warganya mengkonsumsi non beras sebagai bahan makanan pokok justru ‘dihabisi’. Pemerintah dalam persepektif ini adalah sebagai subyek yang mentransformasi rakyat menjadi sekdar objects, recipients, clients atau participant.[10]
Negara ini tidak pernah berhenti untuk mengeksploitasi kekayaan bumi Papua. Paradigma sentralisasi pembangunan selalu saja mengorbankan Papua. MIFEE jelas-jelas bukan proyek pembangunan di Papua. Dia lebih mirip proyek penghancuran. Sungguh ironis, ini mengulang bagaimana proyek pertambangan seperti Freeport di Papua justru tidak dinikmati sang pemilik rumah. Ini bukti kesekian kalinya bahwa Indonesia menjajah Papua.[]
Tolak pembangunan MIFEE!
[1] Daniel S. Stephanus dalam Ancaman Krisis Pangan Global yang terbit di Majalah Dimensi edisi 36 tahun 2016
[2] http://www.wwf.or.id/?40183/12-Juta-Ha-Lahan-Merauke-untuk-Lumbung-Pangan-Nasional diakses 14 Februari 2017 pukul 05.28
[3] Takeshi Ito, Noer Fauzi Rachman, Laksmi A. Savitri, Naturalizing Land Dispossesion: A Policy Discourse Analysis of the Merauke Integrated Food and Energy Estate, makalah yang dipresentasikan di Konferensi Internasional: Global Land Grabbing, 6–8 April 2011
[4] https://gutterspit.com/2015/11/06/memperluas-solidaritas-ruang-melawan-ekspansi-i-menonton-the-mahuzes/ diakses 14 Februari 2017 pukul 08.00
[5] Andre Barahamin dalam Hikayat Beras Pemangsa Sagu: Etnosida Terhadap Malind-Anim Melalui Mega Proyek MIFEE dalam http://indoprogress.com/2015/10/hikayat-beras-pemangsa-sagu-etnosida-terhadap-malind-anim-melalui-mega-proyek-mifee/
[6] Ibid.
[7] https://awasmifee.potager.org/?p=1073&lang=id diakses 14 Februari 2017 pukul 07.05
[8] Charles Tawaru, Koordinator Greenpeace di Papua dalam https://awasmifee.potager.org/?p=284&lang=id (diakses 14 Februari 2017 pukul 06.09)
[9] Andre Barahamin dalam Hikayat Beras Pemangsa Sagu: Etnosida Terhadap Malind-Anim Melalui Mega Proyek MIFEE dalam http://indoprogress.com/2015/10/hikayat-beras-pemangsa-sagu-etnosida-terhadap-malind-anim-melalui-mega-proyek-mifee/ diakses 14 Feruari 2017 pukul 08.37
[10] Juni Hartanto dalam tulisannya berjudul Tinjauan Kritis Dr. Mansour Fakih terhadap Revolusi Hijau
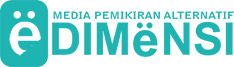
 ‘Nasi’ dan Ancaman Kehancuran Papua">
‘Nasi’ dan Ancaman Kehancuran Papua">