Judul: Pulang
Penulis: Leila S. Chudori
Penerbit: Kepustakaan Populer Gramedia
Kota Terbit: Jakarta, 2012
Tebal buku: viii + 461
ISBN: 13: 978–602-424–275‑6
“Ada kekacauan politik yang bukan sekadar mengalahkan, tetapi merontokkan, kemanusiaan Dimas dan kawan-kawannya, hingga mereka harus memungut kembali serpihan dirinya dan membangun itu semua agar bisa kembali menjadi sekumpulan manusia yang memiliki harkat yang utuh.” (Pulang, h. 203)
Pulang menjadi sebuah novel drama keluarga, persahabatan, cinta, dan penghianat berlatar tiga peristiwa sejarah, yaitu Indonesia, 30 September 1965 (G30S); Paris, Mei 1968; dan Indonesia, Mei 1998.
Novel ini juga menjadi novel sejarah pertama Leila S. Chudori dengan gaya realis-sosial yang sebelumnya dipopulerkan oleh penulis ‘Tetralogi Buru’, Pramoedya Ananta Toer. Melalui ‘Pulang’, Leila telah berhasil mengantongi Penghargaan Kusala Khatulistiwa pada 2013.
Prolog buku ini diawali dengan sudut pandang orang pertama, Hananto Prawiro, yang menceritakan penangkapannya di sebuah tempat foto di Jalan Sabang pada April 1968. Hananto merupakan butir terakhir dari serangkaian perburuan yang dilakukan pasca peristiwa 30 September 1965.
Pada bab pertama dan bab-bab selanjutnya berjudul nama tokoh yang akan mengambil alih cerita dan sub-bab –latar kejadian yang akan diceritakan di dalamnya. Kemudian, ada sebagian kecil cerita yang mengambil sudut pandang orang ketiga untuk menyorot cerita dengan lebih jelas.
Meskipun menerapkan multi-POV (point of view) dan alur campuran, ‘Pulang’ tak akan membuat pembacanya kebingungan saat membaca halaman demi halamannya. Setiap puzzle yang ada akan terjawab seiring berjalannya cerita.
Bab pertama novel ini diambil alih oleh Dimas Suryo, yang menceritakan pertemuan IOJ (International Organization of Journalists) di Santiago sekaligus Konferensi Organisasi Setiakawan Rakyat Asia-Afrika di Peking pada tahun 1966, yang ia ikuti bersama ketiga kawannya; Nugroho, Tjai, dan Risjaf.
Di sini, sosok Hananto Prawiro, roman cinta segitiga antara Dimas, Hananto, dan Surti, dikisahkan secara detail dan puitis. Saat berada di Peking, berita peristiwa G30S sampai ke telinga Dimas dan kawan-kawannya. Status kewarganegaraan mereka dihapus dan masuk dalam daftar orang yang diburu karena mereka bekerja di Kantor Berita Nusantara, kantor berita yang dianggap ‘kiri’ oleh pemerintah.
Setelah menetap dan bekerja di Peking selama beberapa waktu, Dimas mengajak ketiga sahabatnya untuk bertolak ke Eropa. Mereka memilih Prancis setelah mengunjungi berbagai negara di sana. Negara itu dianggap ramah terhadap para korban politik yang kehilangan suaka seperti mereka. Ketika di Prancis, terdengar kabar tentang penangkapan satu per satu sahabat mereka hingga penangkapan Hananto Prawiro.
Di tengah pencarian ‘identitas’, mereka didera rasa bersalah karena satu per satu kawan mereka tumbang, ditangkap, ditembak, atau dihilangkan nyawanya. Untuk bertahan, Dimas dan kawan-kawannya tetap menjalin hubungan dengan orang-orang senasib dari Indonesia yang ada di Eropa. Mereka berempat memungut kembali ‘jati diri’ dengan menyebut dirinya sebagai ‘Empat Pilar’ di restoran ‘Tanah Air’ yang berhasil mereka bangun.
Lintang Utara, anak Dimas Suryo dengan gadis bermata hijau asal Prancis –Vivienne Deveraux menjadi pencerita di bab selanjutnya. Tahun 1998, dua puluh empat tahun setelah kelahirannya, Indonesia menjadi bagian dirinya yang masih terdengar asing dan abstrak. Bagaimana bisa negeri yang menjadi tempat kelahiran sang ayah masih dikuasai oleh satu rezim yang sama setelah berpuluh-puluh tahun.
Lintang yang berada di tahun terakhir pendidikannya di Universitas Sorbonne tengah merencanakan dokumenter untuk tugas akhirnya. Proposalnya tentang imigran Aljazair di Perancis ditolak mentah-mentah oleh dosennya –Monsieur Dupont. Ia justru disarankan untuk membuat dokumenter tentang Indonesia.
Alhasil, Lintang berulang kali mempertanyakan bagaimana memetik Indonesia dari I.N.D.O.N.E.S.I.A. Dan singkat cerita, akhirnya gadis berambut hitam ikal itu bisa menginjakkan kaki ke tanah yang baginya asing, penuh teka-teki, tapi mampu membuat hatinya berdesir tiap kali mendengar cerita tentangnya.
Di Jakarta, le coup de foudre yang menerpa Lintang Utara karena pertemuan pertamanya dengan Alam –anak Surti Anandari dan Hananto Prawiro, diceritakan di bab ketiga ‘Sagara Alam’. Alam adalah seorang aktivis di LSM yang merasakan diskriminasi akibat konsep Bersih Lingkungan yang dijalankan pemerintah Orde Baru.
Di bab ini, dijabarkan pelbagai dampak dari kediktatoran rezim dan stigmatisasi terhadap ‘mereka’ yang sebenarnya tak pernah terlibat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Bagaimana Surti dan ketiga anaknya, keluarga Aji Suryo –adik Dimas, Bimo, dan banyak orang tidak bersalah lainnya harus mendapatkan dampak dari doktrin yang disebarkan penguasa.
Selebihnya, keadaan Jakarta sedang panas; terjadi chaos karena inflasi, penjarahan dan kekerasan yang menyasar keturunan Tionghoa, dan demonstrasi yang kerap dibuat ricuh oleh pihak yang tak dikenal.
***
Mengangkat sisi lain dari peristiwa sejarah dan dampaknya pada orang-orang yang berbeda, menegaskan bahwa Leila hendak memberikan pemahaman tentang sejarah sebagai sesuatu yang absolut.
Selama ini, sekolah selalu menjejali pendidikan sejarah hanya melalui satu sudut pandang yang membentuk indoktrinasi secara kolektif dan pemberian ‘cap’ pada kelompok tertentu sebagai tokoh antagonis yang diciptakan oleh penguasa.
Padahal di luar semua itu, ada banyak kebenaran yang tak tertulis namun jelas dirasakan oleh orang-orang yang terlibat langsung dalam peristiwa sejarah itu. Selebihnya, masih banyak sebab-akibat dalam sejarah Indonesia yang masih abu-abu hingga saat ini.
Ada banyak sisi yang harus digali untuk memahami satu konteks sejarah. Pendukung PKI mungkin pernah begitu agresif dan ganas dalam menghajar lawannya. Namun apa yang terjadi setelah 30 September, konsep ‘Bersih Diri dan Bersih Lingkungan’ membuat perburuan dan pembantaian dianggap sebagai suatu yang wajar oleh mayoritas orang negeri ini.
Pemerintah yang seharusnya mencerdaskan dan melindungi segenap warganya –baik mayoritas maupun minoritas, justru menormalkan serangkaian peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terbesar dalam sejarah Indonesia pasca-merdeka.
Selain sejarah, Leila juga mengangkat segala macam tentang Indonesia sehingga membuat pembacanya bisa memetik Indonesia dari I.N.D.O.N.E.S.I.A. Bicara ‘Pulang’ tak hanya tentang karya sastra yang mengangkat kisah sekelompok jurnalis yang dianggap ‘kiri’, namun di dalamnya juga ada bahasan tentang kuliner, wayang, seks, hingga spiritualitas. Dimas Suryo sebagai chef di restoran ‘Empat Pilar Tanah Air’ meromantisi makanan bak puisi yang memiliki ruh di setiap hidangannya.
“Buat saya, memasak sebuah hidangan sama seriusnya seperti menciptakan sebuah puisi. Setiap huruf berloncatan mencari jodoh untuk membentuk kata; setia kata meliuk, melesat, dan mungkin saling bertabrakan dan rebutan mendapatkan jodoh untuk membentuk kalimat yang berisi sekaligus memiliki gaya puitik. Setiap huruf mempunyai ruh, mempunyai nyawa, dan memilih kehidupannya sendiri.”
Cerita wayang, The Mahabharata, menjadi sorotan yang sering dibahas oleh Lintang Utara untuk menggambarkan sosok ayahnya, Dimas Suryo. Ekalaya dan Bima yang menjadi tokoh wayang favorit Dimas menggambarkan bagaimana kepribadiannya.
Bima begitu setia pada Drupadi, seperti Dimas yang begitu setia kepada negeri dan tanah airnya. Bagi Dimas, Indonesia adalah rumah yang paham bau, bangun tubuh, dan jiwanya. Ia bahkan menyimpan setoples cengkeh dan kunyit di apartemennya demi tetap bisa merasakan bau Indonesia di tengah gemerlap Kota Cinta –Paris.
Dimas layaknya tokoh Ekalaya ditolak oleh Dorna. Ia ditolak oleh pemerintah Indonesia, tetapi dia tidak ditolak oleh negeri dan tanah airnya.
Leila turut mengangkat tentang peringatan hari Kartini yang kerap dirayakan sebagai acara seremonial belaka. Selama ini, peringatan emansipasi justru hanya dimaknai sebagai pengenaan kebaya, acara berkumpul dan makan bersama tanpa mengingat cita-cita Kartini yang tertuang dalam surat-suratnya.
Selain pesan sejarah yang kuat, apa yang dikatakan tiga diplomat muda –Raditya, Hans, dan Yos dalam novel ini, saya rasa mewakili salah satu tujuan dari reformasi sekaligus pemaknaan dari ‘memanusiakan manusia’ itu sendiri.
Bahwa setiap orang memiliki otak dan pemikirannya masing-masing, karena itu tak seharusnya seorang manusia didikte oleh manusia lain. Setiap orang memiliki hak untuk mengekspresikan diri dan percaya terhadap apa yang ia percayai, tanpa diskriminasi dan tanpa intervensi dari penguasa atau pihak manapun.“Politik tak pernah sederhana. Pergumulan ideologi adalah pembungkus atau sekadar pretensi untuk kegairahan akan kekuasaan.” –Vivienne Deveraux (Pulang, h. 204)
Penulis: Nandya
Editor: Ulum
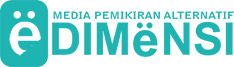
 “Pulang”: Memungut Serpihan Diri yang Direnggut Penguasa">
“Pulang”: Memungut Serpihan Diri yang Direnggut Penguasa">